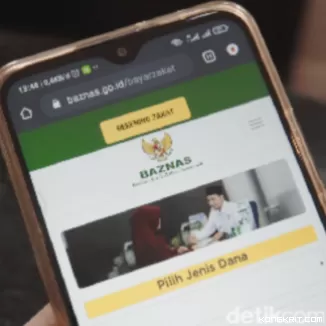Di sudut sebuah kota kecil, di balik deretan bangunan tua, seorang perempuan muda duduk termenung di sebuah bangku kayu yang mulai lapuk. Wajahnya cantik, rambutnya tergerai panjang, dan kulitnya seputih susu. Tapi hari itu, kilau di matanya telah sirna.
Anda mungkin akan terpikat jika melihatnya sekilas. Bukan hanya karena parasnya yang memesona, tetapi juga kelembutan tutur katanya yang membuat setiap orang merasa nyaman. Namun, siapa sangka, di balik pesonanya, ada cerita cinta yang berakhir dengan luka.
Dia, perempuan muda dari pelosok desa, pernah jatuh hati pada seorang pria yang berbeda jauh darinya. Pria itu, seorang duda beranak tiga, hidup dengan luka yang tak kalah dalam—ditinggal mati istri tercinta saat melahirkan anak bungsu mereka.
Cinta mereka seperti dongeng; perbedaan usia dan status sosial seolah tak berarti. Anda bisa melihat betapa kuat ikatan mereka, bagaimana mereka saling berjanji untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain.
Tapi, harapan itu pupus. Orang tua perempuan itu menolak hubungan mereka mentah-mentah. “Apa jadinya masa depanmu?” tanya sang ayah dengan nada tajam. Ibunya hanya menangis, tak mampu berkata-kata. Dan di sinilah dia kini, sendirian, memeluk impiannya yang telah hancur berkeping-keping.
Coba bayangkan, bagaimana rasanya memikul beban itu? Dia meninggalkan pekerjaannya yang sederhana namun cukup berarti. Gajinya mungkin kecil, tapi itu membantu membayar kontrakan kecilnya di kota dan mengirim sedikit uang ke kampung untuk meringankan beban orang tua. Kini, dia merasa telah mengecewakan mereka semua, termasuk dirinya sendiri.Di tengah lamunan, matanya berkaca-kaca. Anda bisa melihatnya setitik air mata mengalir di pipinya yang halus. Ia mengusapnya perlahan, seolah mencoba menahan gelombang emosi yang menyeruak. Tapi pertanyaan itu terus menghantui; Mengapa aku jatuh ke dalam pelukan seorang duda beranak tiga?
Hari itu, dia memutuskan sesuatu. Anda mungkin tak akan percaya betapa beratnya keputusan itu. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan pakaiannya ke dalam sebuah koper tua. Dia akan pulang ke desa. “Aku harus menemui ibu,” bisiknya lirih.
Jika Anda berdiri di sampingnya saat itu, Anda bisa merasakan kesedihannya. Setiap langkah menuju pintu seperti membawa beban berton-ton. Tapi dia tahu, ini yang terbaik. “Maaf,” katanya pelan, entah ditujukan kepada siapa—kepada pria itu, kepada orang tuanya, atau kepada dirinya sendiri.
Dia menatap sekeliling untuk terakhir kali, mengingat kenangan yang pernah ia ukir di kota ini. Dengan senyum tipis yang dipaksakan, dia melangkah pergi, meninggalkan cinta dan mimpi yang pernah ia peluk erat.